Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat
Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.
Produk
Perancangan Undang-Undang
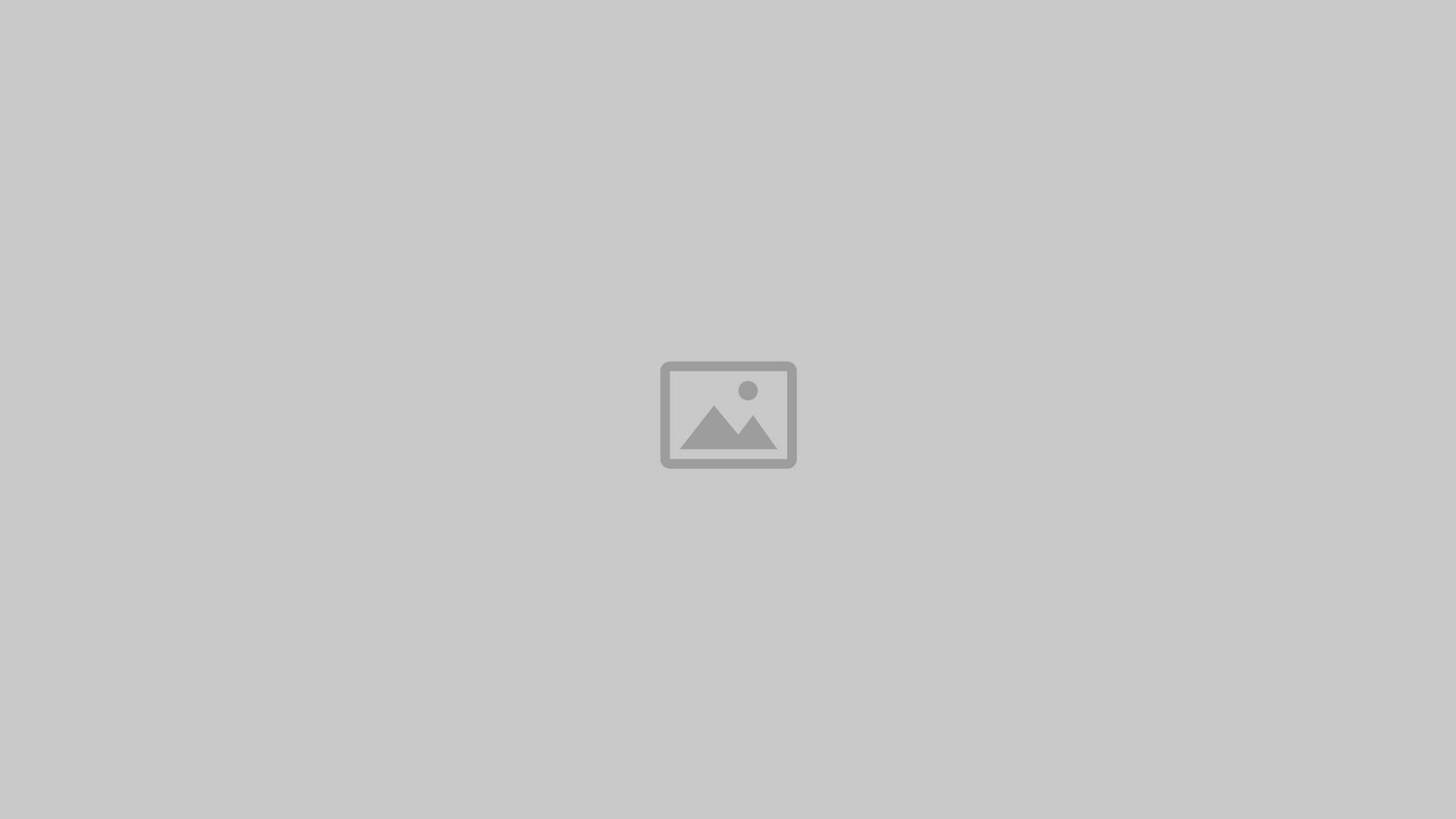
KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI
Tanggal
2022-12-06
Tim Penyusun
1937
1949
2352
2364
27000028
1913
Pengelolaan keuangan haji erat kaitannya dengan penyelenggaraan ibadah haji bagi umat muslim. Hal ini terjadi karena ibadah haji yang merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Dikarenakan waktu tunggu untuk melaksanakan ibadah haji terbilang cukup lama dikarenakan kuota haji yang terbatas menyebabkan banyak jemaah haji yang mendaftar haji terlebih dahulu. Besarnya pendaftar ibadah haji ini lantas membuat penumpukan dana haji yang cukup besar juga. Maka dari itu diperlukan kepastian hukum yang menjamin pengelolaan keuangan haji untuk penyelenggeraan ibadah haji. Perlindungan dan jaminan pengelolaan keuangan haji umat muslim dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Haji (UU Pengelolaan Keuangan Haji). UU Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan sebagai payung hukum guna menjamin pengelolaan keuangan haji di Indonesia dimana pengelolaan tersebut dilaksanakan oleh suatu lembaga pengelola keuangan haji.
Selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak UU Pengelolaan Keuangan Haji diundangkan belum terdapat permohonan pengujian undang-undang sehingga norma-norma dalam UU Pengelolaan Keuangan Haji keseluruhannya tetap berlaku hingga saat ini. Namun, dalam pelaksanaan UU Pengelolaan Keuangan Haji masih terdapat beberapa permasalahan, baik dari sisi substansi, kelembagaan, sarana dan prasarana, budaya hukum, serta dari sisi pemenuhan nilai-nilai Pancasila. Permasalahan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Haji yang terjadi selama ini antara lain yaitu adanya perbedaan pengaturan UU Pengelolaan Keuangan Haji dengan UU terkait lainnya; kurangnya sinergitas antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan Kementrian Agama maupun DPR dalam hal penetapan biaya ibadah haji ; belum optimalnya pengawasan eksternal untuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan belum optimalnya peran serta masyarakat. Hal ini menyebabkan belum optimalnya fungsi dan tujuan penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana diamanatkan oleh UU Pengelolaan Keuangan Haji. Selama berlakunya UU Pengelolaan Keuangan Haji, terdapat beberapa undang-undang yang secara substansial terdapat perbedaan pengaturan dengan UU Pengelolaan Keuangan Haji, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU
Perbankan Syariah);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PIHU);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).
Aspek Substansi Hukum
a. Perbedaan Pengaturan dalam UU Pengelolaan Keuangan Haji dan UU Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah
1) Perbedaan Definisi Penyelenggaraan Ibadah Haji
Terdapat perbedaan pengaturan antara Pasal 1 angka 9 UU PKH dengan
Pasal 1 angka 3 UU PIHU. Pasal 1 angka 9 UU PKH, menyebutkan Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah “…rangkaian kegiatan pengelolaan
pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji…”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 UU PIHU, menyebutkan Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah “…kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan…”. Merujuk pada perbedaan dari kedua definisi tersebut menunjukkan bahwa UU PKH masih mengikuti rezim UU 13/2008 yang telah dicabut dengan UU PIHU yang berlaku sejak 29 April 2019.
2) Perbedaan Definisi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
Ketentuan Pasal 1 angka 12 UU PKH dengan Pasal 1 angka 13 UU PIHU terkait dengan definisi biaya penyelenggaraan ibadah haji menimbulkan perbedaan pemahaman pada implementasinya. Terhadap persandingan kedua definisi tersebut dipahami ketentuan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dimaksud dalam UU PKH tidak sejalan dengan yang terdapat dalam UU PIHU, melainkan pendefinisian biaya penyelenggaraan haji di dalam UU PKH justru memiliki makna Bipih sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 12 UU PIHU. Hal ini memberikan sebuah efek domino terhadap sumber BPIH yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PKH dengan Pasal 44 UU PIHU, sehingga menimbulkan ketidakjelasan serta bertentangan dengan aspek transparan di dalam UU PKH.
b. Penggabungan UU Pengelolaan Keuangan Haji dan UU Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah Dengan Metode Omnibus Law
Persoalan disharmoni pengaturan maupun ego sektoral penyelenggaraan keuangan haji dan pengelolaan keuangan haji menyebabkan tidak efektifnya penyelenggaraan haji. Hal ini terutama dalam melakukan pengelolaan haji yang belum selaras dengan arah kebijakan penyelenggaraan haji. Sehingga, diperlukan adanya penyelarasan UU PKH dan UU PIHU. Salah satu penyelesaian yang dapat dilakukan untuk meyelaraskan keduanya, dapat dilakukan dengan menggabungkan kedua undang-undang tersebut dengan menggunakan metode omnibus law atau dengan membentuk 1 (satu) undang-undang baru yang bersifat
payung hukum (umbrella act) bagi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
2. Aspek Struktur Hukum
a. Mitigasi Risiko atas Tanggung Renteng dalam Penempatan dan/atau Investasi Keuangan Haji
Penempatan dan/atau investasi keuangan haji merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan haji untuk memperoleh nilai manfaat yang lebih besar. Namun, adanya batasan prinsip kehati-hatian dan keamanan membatasi BPKH dalam melakukan investasi keuangan haji. Hal ini juga disebabkan karena adanya pertanggungjawaban tanggung renteng apabila terjadi kesalahan atau kealpaan dalam investasi. Akibatnya BPKH hanya melakukan investasi pada aset-aset yang berisiko rendah untuk mengurangi kemungkinan kerugian.
b. Pelibatan BPKH Dalam Penentuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
Penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya dibiayai dari keuangan haji yang bersumber tidak hanya dari setoran calon Jemaah haji, tetapi juga bersumber dari nilai manfaat dan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya. Biaya penyelenggaraan ibadah haji tersebut ditetapkan setiap tahunnya oleh Presiden melalui mekanisme pengusulan oleh Kemenag kepada DPR RI. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022, biaya penyelenggaraan ibadah haji reguler terjadi kenaikan biaya masyair sekitar Rp. 1,5 triliun, dan kenaikan tersebut diluar prediksi perhitungan Kemenag. Dalam pelaksanaannya selama ini, BPKH sebagai badan yang mengelola keuangan haji tidak pernah dilibatkan sejak awal dalam penyusunan perhitungan biaya penyelenggaraan haji. Hal ini yang menyebabkan terjadinya perhitungan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang kurang tepat.
c. Perlunya Penyesuaian Kewenangan BPKH
Aspek pengelolaan keuangan haji yang menjadi kewenangan BPKH pada praktiknya dianggap tumpang tindih/duplikasi peran dengan Dirjen PHU Kemenag. Kewenangan yang dilaksanakan BPKH selama ini dianggap dilakukan diluar kewenangannya, seperti mengusulkan anggaran tandingan dan melakukan pembahasan kontrak nego pesawat (penerbangan). Berdasarkan Pasal 22 UU PKH telah menugaskan kepada BPKH yang diantaranya adalah pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan haji. Selanjutnya Pasal 24 huruf b UU PKH juga telah memberikan kewenangan kepada BPKH untuk melakukan kerja sama dengan lembaga lain. Atas dasar ketentuan tersebut, kewenangan BPKH dalam mengusulkan anggaran dan melakukan pembahasan kontrak nego pesawat tidak bertentangan dengan UU PKH. Namun demikian, hal tersebut dianggap sebagai permasalahan akibat adanya tumpang tindih/duplikasi peran kewenangan antara BPKH dengan Kemenag yang berasal dari ketidaktegasan batasan kewenangan BPKH dalam tindakan yang beririsan dengan pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji.
d. Pengawasan Eksternal Terhadap BPKH
Pasal 54 UU PKH mengamanatkan pengawasan terhadap BPKH dilakukan secara internal dan eksternal. Pada sisi pengawasan dari pihak eksternal ditemukan catatan belum terpenuhinya aspek syariah. Hal ini ditandai dengan standar akutansi yang masih terbatas pada standar akutansi negara, meskipun terdapat kewenangan BPK untuk melakukan audit tersebut, tetapi BPKH yang merupakan entitas dengan keunikan. Sebagaimana das sollen BPKH pada dasarnya bersifat nirlaba, namun secara das sein di saat bersamaan BPKH turut mengelola dana jemaah haji melalui pendekatan korporatif.
3. Aspek Pendanaan
a. Penempatan Investasi Keuangan Haji Pada Sektor Pelayanan Haji
BPKH diberikan kewenangan melakukan penempatan dan/atau investasi sebagaimana diatur dalam UU PKH dengan tetap berpegang pada prinsip syariah, optimal, aman dan likuiditas sehingga tidak ada pembatasan dalam UU PKH terkait dengan investasi yang akan dilakukan oleh BPKH. Pembatasan yang ada hanya dalam hal kuota atau jumlah batas maksimum investasi langsung. Pengelolaan dana haji saat ini telah bergeser dari fokus sektor perbankan syariah dan memindahkannya ke instrumen investasi lain yang dianggap mampu memberikan imbal hasil yang lebih optimal, namun jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan Pasal 27 PP PKH.
b. Distribusi Nilai Manfaat Dana Haji Jemaah Tunggu Untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji di Tahun Berjalan
Skema pembiayaan haji saat ini masih menggunakan skema distribusi nilai manfaat (biasa disebut subsidi dana haji) yang diambil dari hasil pengelolaan dana haji milik jemaah yang belum berangkat. Dari data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tahun 2021, terdapat distribusi nilai manfaat yang diberikan kepada jemaah sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total BPIH, sementara hasil pengelolaan keuangan haji rata-rata dalam 1 (satu) tahun hanya mencapai 7% (tujuh persen) sampai 8% (delapan persen). Skema distribusi nilai manfaat dan minimnya hasil pengelolaan keuangan haji/nilai manfaat berpotensi memberatkan pengelolaan keuangan haji dan dapat memicu risiko likuiditas keuangan haji. Besaran distribusi nilai manfaat dana haji yang mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total BPIH mempengaruhi kemampuan finansial secara rill serta dapat mempengaruhi syarat istithaah jemaah haji. Kondisi demikian dikhawatirkan memicu pengelolaan keuangan haji mengarah kepada Skema Ponzi.
4. Aspek Budaya Hukum
a. Tanggapan Masyarakat Atas Usulan Nama Calon Anggota BPKH
UU PKH telah membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam pemilihan calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas BPKH yang telah memenuhi prinsip transparan karena membuka peluang turut dilibatkannya masyarakat sebagai pemilik dana haji, dan tentu akan meningkatkan kepedulian masyarakat atas pengelolaan keuangan haji. Namun demikian, masyarakat masih belum mengetahui adanya mekanisme penerimaan atau respon dari tanggapan masyarakat atas calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas BPKH, dan juga tidak pernah dimintai tanggapan sebagai bagian dari masyarakat.
b. Kurangnya Sosialisasi Pengeloaan Dana Haji Kepada Calon Jemaah Haji
Pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan keuangan haji hanya sebatas besaran Bipih yang ditetapkan DPR RI dan Kemenag, dan tidak mengetahui mengenai pengelolaan keuangan haji. Hal ini dikarenakan Kemenag selaku operator maupun BPKH selaku pengelola keuangan haji kurang memberikan sosialisasi dan tidak mematuhi prinsip keterbukaan kepada calon jemaah haji terkait dana pengelolaan keuangan haji. Di sisi lain, selain kurangnya sosialiasi penyebab ketidaktahuan masyarakat dikarenakan sikap abai masyarakat terhadap pengelolaan keuangan haji yang berimplikasi pada pengetahuan masyarakat terhadap jumlah nilai manfaat dari setoran awal yang diperoleh setiap calon jemaah haji. Hal demikian mempengaruhi pengetahuan masyarakat terhadap jumlah nilai manfaat dari setoran awal yang diperoleh calon jemaah haji. Seharusnya BPKH atau Kemenag memberikan kemudahan dan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat melalui platform digital untuk dapat mengetahui optimalisasi atau nilai manfaat dari setoran awal calon jemaah haji.
5. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila
Pancasila sebagai dasar negara mempunyai nilai-nilai yang harus diterapkan dalam bernegara. Munculnya berbagai persoalan menunjukkan bahwa telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam penerapannya. Oleh karena itu, pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan untuk menyelaraskan tujuan negara. Dalam konteks materi muatan dalam UU PKH perlu untuk ditinjau kembali, terutama berkaitan dengan persoalan persoalan yang menimbulkan adanya pertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, antara lain:
a. Aspek Substansi
1) Adanya perbedaan definisi dalam penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana pengaturan dalam Pasal 1 angka 9 UU PKH dan Pasal 1 angka 3 UU PIHU memberikan dampak ketidakselarasan dalamimplementasinya. Ketidakselarasan menyebabkan adanyapertentangan dengan sila keempat Pancasila, sebab pada dasarnya pembentukan suatu aturan harus memperhatikan hikmat kebijaksanaan.
2) Perbedaan definisi BPIH dalam Pasal 1 angka 12 UU PKH dengan Pasal 13
UU PIHU, menyebabkan adanya multitafsir. Ketidakharmonisan pasal pasal tersebut menimbulkan ketidakselarasan dalam pelaksanaannya, terutama berkaitan dengan pemaknaan Biaya penyelenggaraan haji. Sehingga, hal ini perlu diselaraskan agar sejalan dengan nilai-nilai
Pancasila, terutama berkaitan dengan Sila Kelima Pancasila.
b. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan
1) Pengawasan terhadap BPKH dilakukan secara internal dan eksternal. Adapun pengawasan internal dilaksanakan oleh Dewan Pengawas BPKH, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK. Namun, hingga saat ini belum ada pengawasan eksternal yang khusus mengawasi standar pelaksanaan akuntansi yang berbasis syariah. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penambahan mekanisme audit yang diserahkan kepada pihak yang telah tersertifikasi syariah. Hal ini mengingat rentanya praktik riba dalam pasar keuangan, yang tentu saja menimbang pada prinsip-prinsip dalam UU PKH, maka bertentangan dengan sila Pertama Pancasila.
2) Pasal 53 ayat (1) UU PKH rentan terjadi penyalahgunaan kekuasaan terhadap tanggung jawab renteng akibat ketiadaan sanksi. Hal ini tidak sesuai dengan nilai sila keempat Pancasila. Selain itu, sangat jelas bahwa Pasal 53 ayat (2) UU PKH telah mengatur pengecualian dari tanggungjawab renteng berdasarkan indikator/alasan tertentu. Namun, di sisi lain UU PKH maupun ketentuan turunanya tidak ada memberikan mekanisme yang spesifik untuk menjelaskan mengenai poin-poin ataut rincian guna lepas dari tanggung jawab tanggung renteng.
1. Dalam aspek Substansi Hukum, diperlukan:
a. Harmonisasi rumusan definisi penyelenggaraan ibadah haji dalam Pasal 1 angka 9 UU PKH dengan Pasal 1 angka 3 UU PIHU.
b. Harmonisasi pengaturan terkait rumusan istilah BPIH dan Bipih pada Pasal 1 angka 12 UU PKH dengan Pasal 1 angka 12 UU PIHU diikuti pengaturan terkait sumber BPIH dalam Pasal 7 ayat (1) UU PKH dengan Pasal 44 UU PIHU.
c. Pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan penyatuan UU PKH dan UU PIHU dengan metode omnibus law atau dengan membentuk 1 (satu) undang-undang baru (umbrella act) penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sebagai bentuk penyelarasan materi muatan maupun kelembagaan dalam penyelenggaraan haji dan pengelolaan dana haji.
2. Dalam aspek Struktur Hukum/Kelembagaan, diperlukan:
a. Mendorong BPKH untuk melakukan penempatan dan/atau investasi keuangan haji pada sektor high risk dengan berdasarkan mitigasi risiko yang telah ditetapkan sebagai jaring pengaman potensi kerugian.
b. Pelibatan BPKH dalam penyusunan perhitungan biaya penyelenggaraan ibadah haji hingga penetapannya agar dapat mengantisipasi kenaikan biaya masyairdengan menyediakan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan ibadah haji secara cepat dan tepat.
c. Tugas BPKH yang dilaksanakan untuk menjalankan kewenangannya baik yang bersinggungan dengan Kemenag maupun kewenangan-kewenangan lainnya perlu diinventarisir, dipisahkan secara tegas tugas dan kewenangannya, serta diatur secara jelas dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
d. Pelibatan KAP sebagai pengawas eksternal supaya terpenuhi prinsip syariahdengan penggunaan standar akutansi syariah.
3. Dalam aspek Pendanaan, diperlukan:
a. Pengaturan kembali penempatan dan/atau investasi dana haji pada sektor-sektor yang terkait langsung dengan pelayanan haji seperti hotel/pemondokan, pesawat, dan ready meal and services sehingga dapat menghemat biaya penyelenggaran haji dan umrah yang selama ini masih bergantung pada provider di Arab Saudi.
b. Nilai setoran awal calon jemah haji perlu dinaikkan agar dapat menyeleksi calon jemaah haji yang istitha’ah (mampu secara finansial), namun perlu memperhatikan kemampuan seluruh masyarakat muslim Indonesia. Selain itu, perlu optimalisasi investasi keuangan haji dengan instrumen investasi langsung maupun investasi tidak langsung agar menghindari pengelolaan keuangan haji menjadi Skema Ponzi.
4. Dalam aspek Budaya Hukum, diperlukan:
a. Sosialisasi Pasal 37 UU PKH secara masif dan komprehensif dengan melibatkan lebih banyak media terutama media-media besar nasional, agar informasi dapat diterima secara lebih luas dan mendalam oleh masyarakat.
b. Sinergitas antara BPKH, Kemenag, serta Bank Penerima Setoran untuk
memberikan sosialisasi edukasi dan diseminasi yang berkelanjutan perihal
pengelolaan keuangan haji kepada calon jemaah haji.
5. Dalam aspek Pengarustamaan Nilai-Nilai Pancasila, diperlukan:
a. Aspek Substansi
Perlu untuk mengharmonisasikan definisi agar tercipta kepastian hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji, sehingga secara penegakan hukum dan penerapan hukumnya tidak terjadi mis-komunikasi dan mis-interpretasi.
b. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan
1) Perlu menambahkan auditor syariah yang telah tersertifikasi guna melakukan audit atas akuntansi BPKH dalam pengelolaan keuangan haji.
2) Pengaturan terkait tanggung renteng masih diperlukan guna memberikan pertanggungjawaban bagi BPKH dalam melaksanakan penempatan dan/atau investasi dengan hati-hati. Hal tersebut penting karena aturan tanggung renteng Pasal 53 UU PKH memberikan syarat-syarat pengecualian untuk lepas dari tanggungjawab ini.
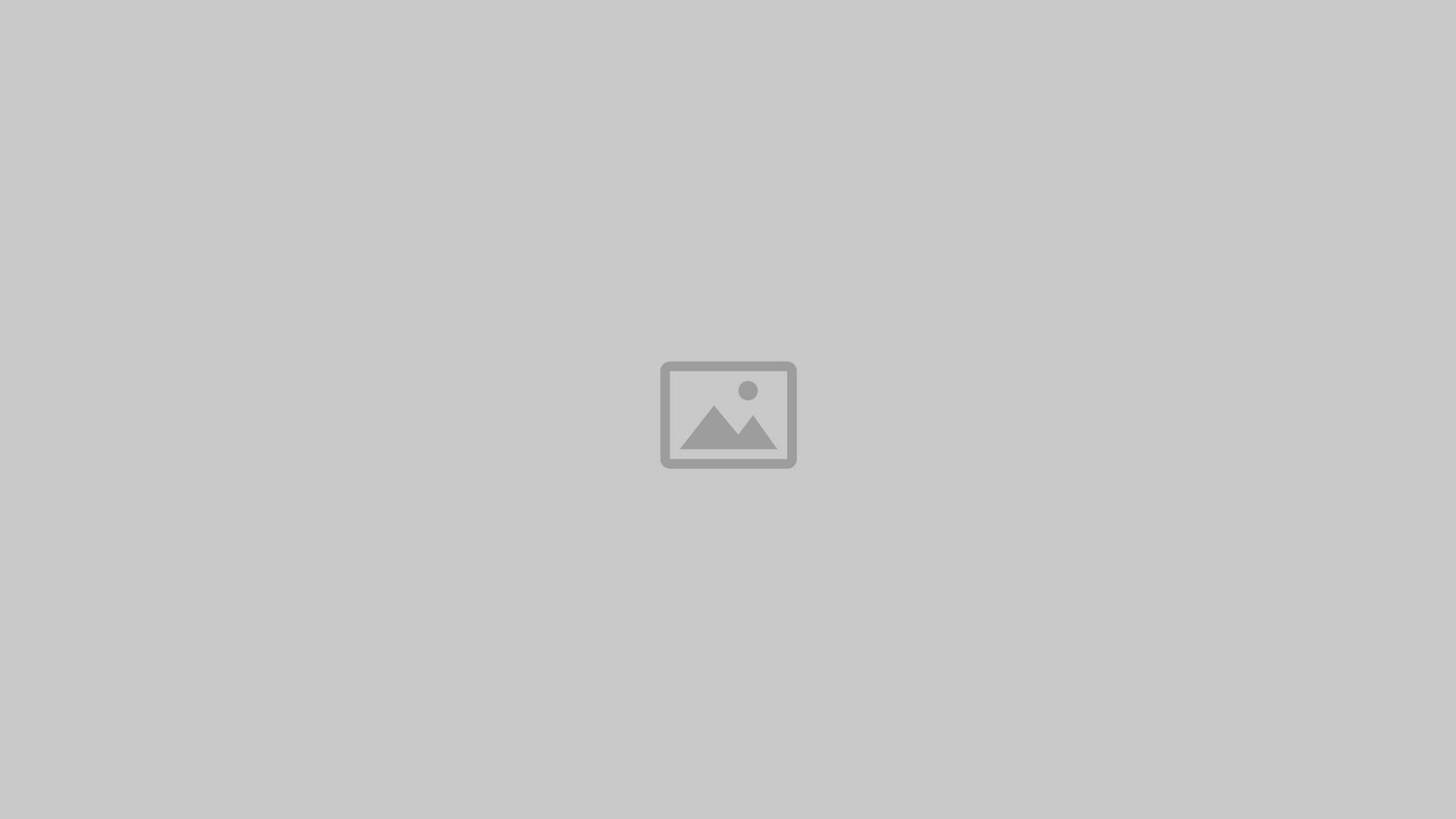
KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Tanggal
2022-10-04
Tim Penyusun
1913
1938
1945
22000024
29000001
2Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan.
Selama kurang lebih hampir 8 (delapan) tahun dengan beberapa kali perubahan, sehingga perlu dilakukan pembaharuan agar substansi di dalam UU 7/2014 dapat memberikan kepastian hukum yang lebih luas kepada masyarakat. Selama berlaku, UU 7/2014 memiliki beberapa isu yang terjadi antara lain: permasalahan terkait pengaturan perdagangan melalui sistem elektronik, masih terdapat beberapa peraturan pelaksana yang belum diterbitkan oleh Pemerintah, pelanggaran terhadap larangan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting pada saat terjadi kelangkaan barang dan gejolak harga, belum optimalnya peran pemerintah dan pemda dalam pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dalam memberikan perlindungan dan pengamanan perdagangan, permasalahan pelaksanaan pengendalian perdagangan luar negeri yang diatur oleh pemerintah pusat, implementasi pelabelan SNI terhadap barang perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah yang multisektoral, tidak memadainya dana untuk mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing, tingkat kepatuhan pelaku usaha baik konvensional maupun yang menggunakan PMSE, dan peningkatan peran serta masyarakat. Selain itu terdapat potensi disharmoni pengaturan UU 7/2014 dengan pengaturan lainnya.
1. ASPEK SUBSTANSI HUKUM
a. Permasalahan Terkait Pengaturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Perkembangan dalam perdagangan saat ini tidak hanya melakukan kegiatan perdagangan secara konvensional namun sudah berkembang lebih jauh dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi yang ada saat ini, perkembangan tersebut tentu saja akan berdampak positif dalam perkembangan perekonomian sehingga saat ini perdagangan dengan sistem elektronik marak dilakukan atau lebih dikenal dengan e-commerce. Dalam UU Perdagangan pengaturan terkait hal tersebut diatur dalam Pasal 65 UU Perdagangan yang mengatur terkait dengan PMSE. Dengan begitu besarnya potensi e-commerce di Indonesia tentu saja memerlukan kesiapan baik itu dalam hal infrastruktur dan juga regulasi yang mengatur kegiatan e-commerce tersebut.
Permasalahan dan tantangan dalam PMSE yang ditemui antara lain belum adanya pengaturan yang jelas terkait bisnis model PMSE khususnya bisnis lokapasar, indikasi praktik white labelling atas produk UMKM, belum adanya pengaturan atau ketentuan yang jelas bagi Pedagang Luar Negeri, masih ditemukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat, serta masih ditemukannya barang yang dijual di lokapasar yang belum memenuhi standar serta proses pangaduan dan penyelesaian sengketa.
b. Masih Terdapat Beberapa Peraturan Pelaksana Yang Belum Diterbitkan oleh Pemerintah
Peraturan pelaksana merupakan peraturan yang dibentuk atas delegasi dari peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya untuk mengatur hal tertentu. Dalam UU Perdagangan sendiri masih terdapat peraturan pelaksanaan yang belum diterbitkan hingga saat ini yang antara lain diatur dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (4), Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 101 ayat (3) UU Perdagangan. Belum diterbitkannya bebeberapa peraturan pelaksanaan tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya.
c. Perbedaan Pengaturan Antara UU Perdagangan dengan Undang-Undang Lainnya:
1) UU Perdagangan dengan UU Perlindungan Konsumen
Terdapat perbedaan definisi Pelaku Usaha yang ada di UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan memberikan batasan bahwa Pelaku Usaha hanya WNI dan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang dibentuk di wilayah NKRI. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen tidak memberikan batasan demikian dalam pendefinisian Pelaku Usaha. Perbedaan definisi Pelaku Usaha dalam kedua undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Sebab, kegiatan e-commerce tentunya tidak dapat dibatasi oleh aspek teritorial.
2) UU Perdagangan dengan UU JPH
Terdapat perbedaan definisi antara Pelaku Usaha yang diatur dalam UU Perdagangan dengan yang diatur dalam UU JPH. Sebab, definisi Pelaku Usaha dalam UU Perdagangan yang membatasi hanya WNI dan badan usaha yang berkedudukan di wilayah NKRI menjadikan ruang lingkup yang lebih sempit dibandingkan definisi Pelaku Usaha dalam UU JPH. Selain itu terdapat perbedaan pengaturan dalam Pasal 57 ayat (1) UU Perdagangan dengan Pasal 4 UU JPH dalam hal produk yang beredar dimana dalam UU JPH mewajibkan untuk produk yang akan masuk, beredar dan akan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal sementara dalam UU Perdagangan tidak mewajibkan hal tersebut melainkan hanya mensyaratkan untuk memenuhi SNI dan persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Hal tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam implementasinya.
d. Pelanggaran Terhadap Larangan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting Pada Saat Terjadi Kelangkaan Barang dan Gejolak Harga
Pemenuhan barang kebutuhan pokok merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, dalam hal ini pemenuhan barang kebutuhan pokok tersebut termasuk kedalam kebutuhan primer yang mutlak untuk dipenuhi. Menurut Organisasi Buruh Internasional atau ILO (International Labour Organization), kebutuhan primer ialah kebutuhan fisik minim masyarakat, berkaitan dengan kecukupan kebutuhan pokok setiap masyarakat baik masyarakat kaya maupun miskin. Lebih lanjut dalam Pasal 29 UU Perdagangan mengatur terkait dengan larangan bagi pelaku usaha untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadinya kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan. Adanya larangan tersebut tentu saja bertujuan untuk menjamin pemenuhan atas barang kebutuhan pokok terhadap masyarakat.
Dalam tataran implementasi masih banyak terjadi penimbunan barang, karena pengaturan yang belum jelas khususnya terkait dengan jangka waktu, dan volume penimbunan serta pihak yang berwenang menentukan kelangkaan barang gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Meskipun telah ada langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemeritah dan pemerintah daerah dalam mengendalikan barang kebutuhan pokok, namun pada implementasinya masih kerap ditemui pelaku usaha yang menimbun barang kebutuhan pokok tersebut meskipun sudah dilarang sebagaimana pengaturan dalam Pasal 29 UU Perdagangan dan terdapat sanksi apabila melanggar ketentuan tersebut.
2. ASPEK STRUKTUR HUKUM/KELEMBAGAAN
a. Belum Optimalnya Peran Pemerintah Dan Pemda Dalam Pemenuhan Ketersedian Barang Kebutuhan Pokok Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pengamanan Perdagangan
Perlindungan dan pengamanan perdagangan dalam pelaksanaannya masih tejadi fluktuasi harga barang pokok dan barang penting banyak dipengaruhi oleh faktor perekonomian dan geopolitik global, terutama untuk barang bersumber dari impor serta rantai pasok yang belum efektif dan efisien yang dipengaruhi akibat belum tepatnya kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, peran Pemerintah dan Pemerintah Pusat masih belum optimal dalam pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di dalam negeri. Hal tersebut dikarenakan pemerintah dan pemerintah daerah masih belum memiliki informasi ketersediaan pasokan dalam negeri yang valid. Dalam UU Perdagangan sebenarnya sudah mengatur bahwa sistem informasi perdagangan yang terintegrasi dapat menciptakan informasi perdagangan yang real time di seluruh wilayah Indonesia. Masalah yang saat ini dihadapi adalah sistem informasi perdagangan terintegrasi tersebut datanya masih tersebar di berbagai K/L, sehingga masih belum dapat menentukan arah kebijakan yang sesuai sehingga baik pemerintah maupun pemerintah daerah masih harus mengecek persediaan dengan turun ke lapangan secara manual.
b. Permasalahan Pelaksanaan Pengendalian Perdagangan Luar Negeri yang diatur oleh Pemerintah Pusat
Perdagangan Luar Negeri atau Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain . Terkait dengan kegiatan Perdagangan Luar Negeri tersebut diatur secara khusus oleh UU Perdagangan dalam BAB V UU Perdagangan.
Menurut salah satu stakeholder sebagai pelaksana ketentuan-ketentuan tersebut masih terdapat kendala yang terjadi dan ditemukan dalam pelaksanaannya di lapangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan mengatakan bahwa masih terdapat kendala yang terjadi dalam segi pengendalian yaitu terkait lamanya penerbitan Perizinan Berusaha/persetujuan Eksportir dan/atau Importir untuk melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor barang.
c. Implementasi Pelabelan SNI Terhadap Barang Perdagangan
Standardisasi ialah suatu patokan atau pedoman yang digunakan untuk menjadi acuan minimal dalam mencapai keselarasan. Standardisasi disebut sebagai usaha bersama dalam pembentukan sebuah standar. Standarisasi diatur secara khusus dalam Bab VII UU Perdagangan dan dibagi dalam dua bagian yaitu Bagian Kesatu yang berisi mengenai Standarisasi Barang serta Bagian Kedua mengenai Standarisasi Jasa. Terkait Standarisasi Barang, dalam Pasal 57 UU Perdagangan dikatakan bahwa barang-barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi dua syarat, yaitu harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai SNI) yang telah diberlakukan secara wajib; atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
Kewajiban Pelaku Usaha dalam melakukan pemenuhan SNI terhadap suatu barang yang diperdagangkan sudah diatur dengan sangat baik dalam Undang-Undang, namun dalam implementasinya masih terdapat kendala yang terjadi di lapangan. Hal ini disampaikan oleh beberapa stakeholder bahwa implementasi standar pemberlakuan SNI wajib belum terintegrasi secara lengkap atau komperehensif.
d. Pemberdayaan Koperasi Serta Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Yang Multisektoral
Ketentuan terkait Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut diatur secara khusus dalam BAB X UU Perdagangan yaitu pada Pasal 73 UU Perdagangan. Dalam Pasal 73 ayat (1) UU Perdagangan dikatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan.
Pengaturan mengenai Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sudah diatur dengan baik dan jelas dalam UU Perdagangan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang terjadi. Hal tersebut disampaikan oleh para stakeholder baik di pusat maupun daerah sebagai pelaksana ketentuan dan yang mengkaji terkait kendala pelaksanaan ketentuan tersebut. Kendala-kendala tersebut yaitu tumpang tindih kewenangan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha ekspor UMKM, belum terlaksananya pelaksanaan digitalisasi UMKM, dan modal koperasi serta UMKM yang cenderung sedikit.
3. ASPEK PENDANAAN
a. Tidak Memadainya Dana Untuk Mengendalikan Kestersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan/Atau Barang Penting
UU Perdagangan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting yakni Pasal 25 sampai dengan Pasal 34 UU Perdagangan. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut, mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.
Dalam Pasal 10 Perpres 59/2020 mengatur tentang biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, selama ini, sebagian besar Pemerintah Daerah masih bergantung pada anggaran dari pusat termasuk dana dekonsentrasi dalam melakukan upaya peningkatan produksi barang kebutuhan pokok dan barang penting dikarenakan kebijakan perdagangan yang masih merupakan urusan pilihan. Sehingga diperlukan menjamin ketersediaan barang dengan data yang valid dan terintegrasi dengan ketersediaan barang dalam pasar tradisional dan modern.
b. Hambatan Anggaran Dalam Pemberdayaan Perdagangan UMKM di Daerah
Pelaku usaha UMKM merupakan pelaku ekonomi yang tersebar ditengah-tengah masyarakat yang terus berkembang pada era otonomi daerah, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah diatur dalam Bab X Pasal 73 UU Perdagangan. Pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perdagangan dapat berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi dna pemasaran. Akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan akses dan/atau bantuan permodalan. Selain itu, dalam PP 7/2021, terdapat pengaturan mengenai Pemkab/Pemkot memiliki kewenangan melakukan restrukturisasi terhadap koperasi, akan tetapi secara pendanaan dari segi anggaran kemungkinan pemerintah daerah tidak bisa melaksanakannya dikarenakan tidak dianggarkan di mata anggaran tahunan.
4. ASPEK SARANA DAN PRASARANA
a. Sistem Terintegrasi Terkait Data Yang Valid
Sistem informasi perdagangan yang selama ini terlaksana masih tersebar dalam Kementerian/Lembaga masing-masing yang menyediakan data informasi perdagangan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Sistem informasi perdagangan terintegrasi memiliki fungsi untuk mengetahui jumlah pasokan kebutuhan dalam negeri sehingga diharapkan terdapat informasi yang akurat yang tersedia dalam hal memberikan kebijakan yang tepat guna untuk Indonesia setiap waktu. Data yang ada di daerah tersebut harusterintegrasi dan sampai ke Pemerintah agar dapat diketahui kondisi perdagangan nasional secara holistik. Sebaliknya, tidak tersedianya data pasokan yang valid di dalam negeri menjadi salah satu penyumbang kesalahan pemerintah dalam menilai pasokan kebutuhan dan cara untuk mengantisipasinya karena sering kali data yang tidak valid atas keadaan perdagangan di Indonesia membuat pemerintah baru turun ke pasar ketika terjadi kesulitan pasokan dan harga yang tidak stabil. Jika hal ini terus terjadi dikhawatirkan terjadi inflasi yang berdampak luas pada timbulnya resesi ekonomi sebagaimana yang telah dialami oleh berbagai negara lain.
b. Pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing
Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar Pasar Rakyat mempunyai peran yang sangat penting sebagai penggerak perekonomian, sehingga dalam pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitasnya diatur secara khusus dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU Perdagangan. Namun dalam pelaksaannya, masih terdapat beberapa kendala yang terjadi. Kendala tersebut adalah pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat belum menunjukkan skala penilaian yang baik karena masih minimnya penganggaran perbaikan fasilitas dan pembangunan Pasar Rakyat; dan masih terdapat beberapa bangunan Pasar Rakyat yang tidak termanfaatkan secara maksimal.
5. ASPEK BUDAYA HUKUM
a. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha baik Konvensional maupun yang menggunakan PMSE
Pemerintah telah menerbitkan PP 80/2019 pada 24 November 2019. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah e-commerce. PP 80/2019 mengatur pokok-pokok transaksi e-commerce baik dari dalam maupun luar negeri, mencakup pelaku usaha, perizinan, dan pembayaran.
Dalam implementasinya, masih ada kesulitan penerapan dalam hal penyelesaian sengketa khususnya transaksi elektronik yang nilai transaksinya tidak begitu besar, data/informasi barang tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang diterima, dan sanksi administratif tidak berjalan efektif bilamana masyarakat tidak melaporkan. Sedangkan terhadap pelaku usaha yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara benar maka diancam dengan sanksi pidana sebagaimana yang tertulis pada Pasal 115 UU Perdagangan. Selain itu, implementasi penjatuhan sanksi sulit diterapkan.
Selain itu, dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku usaha PMSE sangat sulit mengingat market place telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa berupa pergantian produk apabila produk tidak sesuai. Pelaku usaha e-commerce juga belum memenuhi ketentuan SNI wajib dan pelaku usaha masih kurang mendapatkan sosialisasi berkaitan dengan aturan regulasi sektor perdagangan khususnya mengenai perdagangan melalui sistem elektronik/OSS.
b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Dalam UU Perdagangan belum mengatur tentang Peran Serta Masyarakat. Hal ini merupakan hal sangat penting dikarenakan untuk pembangunan ekonomi di bidang perdagangan demi memajukan kesejahteraan umum seperti pelibatan masyarakat itu sendiri. Dengan melibatkan masyarakat dalam bidang perdagangan, masyarakat dapat membantu Pemerintah dalam melakukan pengawasan ataupun memberikan masukan-masukan terkait dengan kendala-kendala yang terjadi di bidang perdagangan.
6. ASPEK PENGARUSUTAMAAN NILAI-NILAI PANCASILA
Masih terdapat beberapa pengaturan dalam UU Perdagangan yang belum selaras dengan nilai-nilai Pancasila, diantaranya:
a. Definisi Pelaku Usaha dalam UU Perdagangan yang hanya dibatasi kepada WNI saja berpotensi mendiskriminasikan antar pelaku usaha, terutama pelaku usaha luar negeri, sehingga bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila;
b. Ketentuan Pasal 50 dan Pasal 54 UU Perdagangan mengatur larangan pembatasan ekspor dan impor. Namun, frasa “kepentingan umum” dalam Pasal 50 UU Perdagangan tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kriteria yang dimaksud dengan kepentingan umum sehingga menimbulkan multitafsir. Selain itu, frasa “industri tertentu” dalam Pasal 54 UU Perdagangan juga tidak menjelaskan secara tegas mengenai kriteria industri tertentu yang dimaksudkan sehingga menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 50 dan Pasal 54 UU Perdagangan tidak selaras dengan sila ke-5 Pancasila;
c. Pasal 57 dan Pasal 113 UU Perdagangan mewajibkan SNI untuk semua barang yang diperdagangkan dan disertai dengan sanksi apabila pelaku usaha melanggar. Namun, ketentuan ini berpotensi merugikan pelaku usaha UMKM yang masih kesulitan memenuhi kewajiban SNI. Sehingga, ketentuan ini belum selaras dengan sila ke-5 Pancasila;
d. Pasal 67 ayat (3) UU Perdagangan mengindikasikan bahwa tidak adanya aturan tentang perlindungan dan pengamanan bagi pelaku UMKM yang terkena dampak perdagangan bebas sehingga belum selaras dengan sila ke-4 Pancasila.
1. Dalam aspek Substansi Hukum, diperlukan:
a. Perubahan ketentuan Pasal 65 UU Perdagangan terkait PMSE yang di dalam ketentuan perubahan nantinya mengatur terkait:
• Pengaturan mengenai standarisasi produk yang diperoleh dengan PMSE secara cross borde transaction;
• Pengaturan mengenai perdagangan melalui media sosial (social commerce) yang saat ini berkembang melalui platform facebook, Instagram, dan tiktok
• Mengatur mengenai pencegahan dan penindakan terhadap adanya predatory pricing.
• Pengaturan tegas terkait pemblokiran usaha yang menerapkan PMSE tidak sesuai ketentuan hukum supaya lebih efektif.
b. Upaya dari pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pelaksanaan yang menjadi amanat dalam UU Perdagangan agar pelaksanaan UU Perdagangan dapat berjalan efektif;
c. Sinkronisasi dan harmonisasi terkait dengan frasa “Pelaku Usaha” dalam Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan dengan UU Perlindungan Konsumen;
d. Sinkronisasi dan harmonisasi terkait dengan frasa “Pelaku Usaha” dalam Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan dengan UU JPH; dan
e. Penegasan pengaturan terkait dengan kriteria penimbunan dalam Pasal 29 UU Perdagangan agar dapat berjalan dengan lebih efektif.
2. Dalam aspek Struktur Hukum, diperlukan:
a. pengawasan yang ketat terhadap cross border transaction dan selalu meng-update seluruh komoditas bahan baku dan komoditi setiap kebutuhan pokok maupun kebutuhan penting nasional secara berkala khususnya mendekati hari raya yang riskan mengalami kenaikan angka kebutuhan di masyarakat dan menyegerakan pembangunan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi agar dapat menghasilkan informasi perdagangan yang real time disetiap daerah guna menelaah faktor-faktor penyebab dari permasalahan perlindungan dan pengamanan komoditi tertentu serta dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan perdagangan yang tepat.
b. Sinergi dan transparansi dari Pemerintah Pusat dalam proses penerbitan perizinan berusaha/persetujuan ekspor dan/atau impor baik kepada para Eksportir dan/atau Importir maupun kepada Pemerintah Daerah yang menangani hal tersebut. Selain itu, dibutuhkan koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi terkait proses penerbitan perizinan berusaha/persetujuan ekspor dan/atau impor agar tidak terjadinya miss communication antara Pemerintah Daerah dengan Eksportir dan/atau Importir. Sosialisasi terkait informasi proses penerbitan perizinan berusaha/persetujuan ekspor dan/atau impor dapat dilakukan melalui sistem informasi perdagangan dengan menambahkan informasi tersebut kedalamnya. Selain itu menurut Akademisi FH Unnes, Pemerintah perlu melakukan penanganan kegiatan-kegiatan dari perdagangan perbatasan;
c. koordinasi terkait pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan dalam bidang Perdagangan khususnya mengenai Standardisasi Barang ke pasar tradisional, toko modern, toko elektronik, dan pelaku usaha lainnya. Selain itu, dibutuhkan penguatan sosialisasi juga yang dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga terkait dalam melakukan penghimbauan kewajiban dan pentingnya pemenuhan SNI dan pemberian logo SNI dalam suatu barang yang diperdagangkan. Selain itu, menurut Akademisi FH Unnes, permasalahan terkait perizinan misalnya uji produk untuk memenuhi SNI pada suatu barang dikenakan biaya satu persatu sehingga pelaksanaannya selama ini tidak efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan penyederhanaan dalam proses tersebut;
d. Adanya batasan yang jelas terkait kewenangan dalam hal pembinaan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian terkait lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih; melakukan sinergi terhadap pengawasan pelaksanaan kegiatan digitalisasi UMKM yaitu Pemerintah dapat bekerja sama atau berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan hal tersebut; serta Pemerintah harus berupaya lebih keras lagi untuk membantu para pengusaha dalam memberikan kemudahan untuk mendapatkan perizinan membuka usaha di UMKM, membantu produk Koperasi dan UMKM agar dapat menembus pasar, dan memudahkan akses permodalan kepada pelaku Koperasi dan UMKM.
3. Dalam aspek Pendanaan, diperlukan:
a. Komitmen dari Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan barang dengan data yang valid dan terintegrasi dengan ketersediaan barang dalam pasar tradisional dan modern;
b. koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait penyediaan pembiayaan yang bersumber dari APBN dan APBD untuk mendukung UMKM di daerah dan perlunya upaya pemberian pengkhususan syarat (priviledge) dalam hal pelabelan tersebut serta dapat dilakukan dengan memberikan insentif atau pemberian subsidi kepada UMKM.
4. Dalam aspek Sarana dan Prasarana, diperlukan:
a. Peran dari pemerintah untuk mempercepat proses transformasi digital. Percepatan tersebut dapat dilakukan jika kondisi prasyarat penting terpenuhi yaitu tersedianya SDM berkeahlian digital tinggi, infrastruktur digital yang merata, dan juga iklim usaha yang mendukung inovasi dan pertumbuhan perusahaan start up baru.
b. Komitmen dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas Pasar Rakyat termasuk dengan melakukan peningkatan pengawasan terhadap fasilitas Pasar Rakyat.
5. Dalam aspek Budaya Hukum, diperlukan:
a. penguatan pemberian sanksi dan pengawasan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Perdagangan dan memperkuat edukasi terhadap masyarakat selaku konsumen;
b. ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan perdagangan di Indonesia baik itu dalam hal pengawasan dan pelaksanaan kebijakan perdagangan di Indonesia.
6. Dalam aspek Pengarus Utamaan Nilai-Nilai Pancasila, diperlukan:
a. revisi Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan terkait definisi “Pelaku Usaha”, karena tidak selaras dengan Sila Ke-5;
b. revisi Pasal 50 dan Pasal 54 UU Perdagangan terkait perlindungan kepada kepentingan umum baik melindungi pasar dan pelaku usaha, karena tidak selaras dengan Sila Ke-5;
c. revisi Pasal 57 dan Pasal 113 UU Perdagangan terkait kewajiban pemberlakuan SNI untuk barang yang diperdagangkan, karena tidak selaras dengan Sila Ke-5;
d. revisi Pasal 67 ayat (3) UU Perdagangan terkait perlindungan dan pengamanan perdagangan bagi pelaku UMKM, karena tidak selaras dengan Sila Ke-4.
